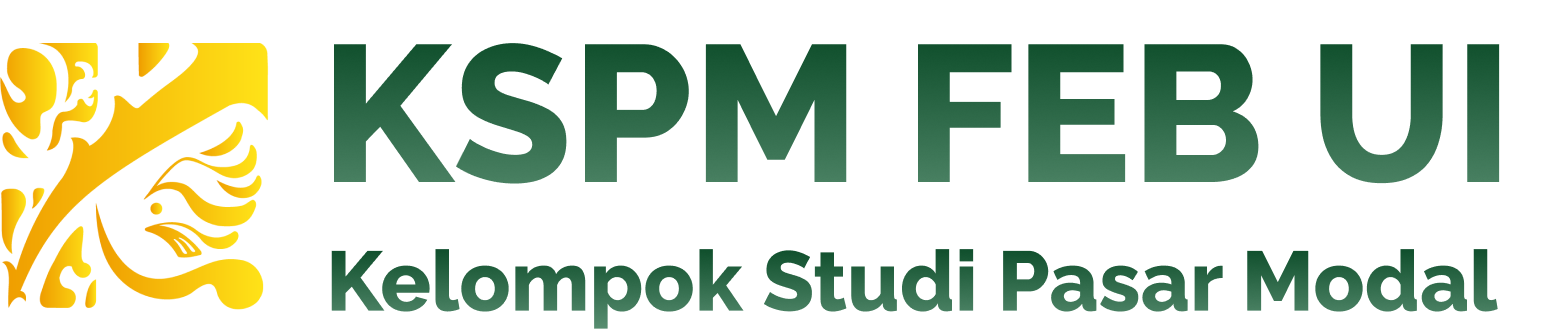Published on August 31st, 2022
Rapid Development in The Midst of Advanced Technology: The Threat of Crimes in Capital Market
Pendahuluan – Kasus PT Jouska
Pada tahun 2021 yang lalu, dunia investasi dan finansial Indonesia kembali diguncangkan dengan kabar negatif terkait dengan kegiatan penghimpunan investasi masyarakat. Kali ini, PT Jouska Finansial Indonesia menjadi tokoh antagonis yang diduga melakukan malpraktik dalam pengelolaan rekening dana investor (RDI). Dalam kasus ini, PT Jouska mengarahkan kliennya untuk menandatangani kontrak yang berisi penyerahan kuasa pengelolaan RDI kepada perusahaan afiliasi Jouska, yaitu PT Mahesa Strategis Indonesia (MSI). Dalam pengelolaan RDI, MSI menggunakan dana yang berhasil terhimpun untuk membeli beberapa instrumen investasi, seperti saham dan reksadana. Salah satu saham yang dibeli oleh MSI adalah saham PT Sentral Mitra Informatika Tbk dengan emiten berkode LUCK.
Malpraktik yang dilakukan oleh MSI menyebabkan adanya lonjakan permintaan terhadap emiten LUCK yang mengakibatkan adanya ilusi ekonomi harga saham. Ilusi yang dimaksud adalah perubahan harga emiten LUCK yang didorong oleh adanya eskalasi pembelian/permintaan secara masif, dan bukan karena valuasi atau prospektus saham. Eksploitasi kebutaan pembeli akan informasi saham tersebut membuat praktik “menggoreng saham” ini dapat dijalankan dengan mulus. Walaupun demikian, tidak ada kegiatan malpraktik yang selalu berjalan mulus. Hal ini terbukti setelah pada tahun 2020, salah satu klien Jouska Indonesia menyadari kerugian akan investasi yang ia lakukan. Kerugian ini disadari ketika klien tersebut menyadari bahwa portofolio sahamnya anjlok 70% dari nominal investasi sebelumnya.
Kasus Jouska bukanlah kasus pertama yang terjadi di ranah investasi dan finansial. Sederetan kasus malpraktik serupa telah tercatat dalam lembaran sejarah yang pada akhirnya menimbulkan tanda tanya mengenai keberlanjutannya. Kecurangan dan malpraktik ini biasa disebut dengan istilah capital market crimes di dalam dunia finansial. Lantas, apa definisi capital market crimes dan bagaimana mekanisme-mekanisme praktik yang telah terjadi di pasar modal?
Mengenal Tindak Kejahatan di Pasar Modal
Seiring dengan perkembangan zaman, dunia pasar modal semakin menunjukkan perkembangan yang pesat. Pasar modal menjadi sebuah alternatif bagi masyarakat dengan return yang menjanjikan dan prospek yang cerah ke depannya. Namun, perkembangan pesat tidaklah lepas dari semakin besarnya pula risiko yang mengintai, yakni risiko kejahatan. Dengan kemajuan teknologi, metode yang digunakan para pelaku kejahatan pun semakin variatif dan kompleks. Menilik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, terdapat tiga jenis tindak kejahatan di pasar modal, yakni penipuan (fraud), manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam (insider trading).
- Penipuan (fraud)
Berdasarkan Pasal 90 huruf c Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), penipuan (fraud) merupakan tindakan membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Larangan ini ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan efek, baik perorangan, korporasi, joint venture, asosiasi, maupun bentuk kelompok lain. Sedangkan, menurut KUHP Pasal 378, penipuan (perbuatan curang) merupakan tindakan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.
Lebih lanjut, pasal 104 UUPM secara implisit menyatakan bahwa pelaku kejahatan penipuan di pasar modal diancam dengan pidana paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000. Apabila membandingkan ancaman kejahatan penipuan di pasar modal dengan tindak kejahatan penipuan lain, seperti pada KUHP Pasal 378 dan 390, ancaman bagi pelaku penipuan di pasar modal lebih berat sebab perdagangan efek merupakan aktivitas yang melibatkan banyak investor serta besarnya jumlah uang.
- Manipulasi Pasar
Dalam Pasal 91 UUPM dijelaskan bahwa setiap pihak dilarang melakukan tindakan manipulasi pasar, yakni tindakan yang bertujuan menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek baik secara langsung maupun tidak langsung. Manipulasi dilakukan untuk mempengaruhi harga sehingga orang yang melakukan manipulasi dapat mencapai pasar yang lebih menguntungkan. Para pelaku manipulasi mendorong pihak lain untuk melakukan tindakan menjual atau membeli suatu saham pada tingkat harga yang diinginkan oleh manipulator. Dalam berbagai kasus, tindakan manipulasi merupakan hal yang sulit bagi para pihak berwenang untuk dideteksi dan dibuktikan, terlebih pada pasar yang berskala besar.
Terdapat dua jenis manipulasi saham yang paling sering dijumpai, yakni pump-and-dump dan poop-and-scoop. Dalam skema metode pump and dump, para pelaku biasanya menyebarkan informasi salah atau menyesatkan untuk menciptakan sentimen positif sehingga akan “memompa” harga saham dan kemudian “membuang” saham dengan menjual saham mereka sendiri saat harga meningkat. Setelah para manipulator ini membuang saham mereka dan berhenti menjual saham, harga saham biasanya turun sehingga para investor kehilangan uang. Sedangkan poop and scoop adalah strategi yang dilakukan para manipulator saham dengan mencoba menggerakan harga pasar sekuritas dengan menyebarkan informasi palsu dan rumor negatif tentang perusahaan (“poop”) sehingga mereka dapat membeli saham pada harga yang lebih rendah (“scoop”). Dengan metode ini, informasi palsu negatif akan menyebabkan para investor menjual saham perusahaan tersebut sehingga harga akan jatuh. Pada saat itulah, para manipulator saham tersebut membeli saham pada harga yang lebih rendah untuk memperoleh keuntungan di kemudian hari. Informasi palsu dan menyesatkan biasanya disebarkan melalui berbagai sumber, mulai dari media sosial, website penelitian investasi, online, surat kabar, majalah, hingga radio.
- Perdagangan Orang Dalam (insider trading)
Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) Pasal 95 hingga 98 melarang perdagangan saham yang dilakukan oleh orang dalam, termasuk pegawai, direktur, pemegang saham utama, atau pihak lain yang memiliki informasi orang dalam untuk mengeruk keuntungan dari jual beli saham. Tindakan insider trading merupakan tindakan ilegal apabila informasi material tersebut masih bersifat nonpublik. Adapun, Informasi material nonpublik sendiri merupakan setiap informasi yang secara substansial dapat mempengaruhi keputusan investor untuk membeli atau menjual saham yang belum tersedia untuk publik.
Kasus Kejahatan Pasar Modal di Indonesia
Kejahatan dan kecurangan dalam ranah finansial, khususnya investasi, bukanlah merupakan hal yang baru dalam ekosistem ekonomi Indonesia. Kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor pemulus kejahatan dan kecurangan finansial dalam beberapa waktu terakhir. Gap yang cukup signifikan antara perkembangan teknologi dan peningkatan kemampuan literasi finansial teknologi (fintech) berhasil dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Data mencatat kejahatan/penipuan siber terjadi sebanyak 16.845 kali dalam medio 2017-2020.
Salah satu bentuk kejahatan finansial yang pernah terjadi di Indonesia adalah insider trading. Insider trading merupakan aktivitas ilegal yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan guna mendapatkan keuntungan pribadi melalui jalan pintas (short swing profit). Aktivitas ilegal yang dimaksud adalah penggunaan data atau informasi perusahaan yang belum disampaikan ke publik dan memiliki pengaruh terhadap keputusan investor serta calon investor.
Contoh perusahaan yang sempat terjerat kasus insider trading adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS). Kasus ini terjadi pada rentang waktu 12 September 2006 sampai 11 Januari 2007. Oknum internal PGAS telah mengetahui informasi rahasia mengenai penurunan volume gas dari 150 MMSCFD menjadi 30 MMSCFD sebelum rilis pers pada tanggal 12 September 2006, dan informasi mengenai tertundanya gas-in pada tanggal 18 Desember 2006. Fakta ini menyebabkan terjadinya aktivitas transaksi saham PGAS pada rentang waktu kasus, yakni 12 September 2006 hingga 11 Januari 2007. Alhasil, kejahatan terselubung ini menyebabkan perubahan pada harga efek PGAS yang bergerak curam sebesar 23,36% dari Rp9.650/saham menjadi Rp7.400/saham.
Berbicara mengenai hukum, praktik insider trading merupakan bentuk pelanggaran hukum pidana menurut pasal 85 sampai dengan pasal 99 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pasal-pasal tersebut dengan jelas mengatur mengenai “Pelaporan dan Keterbukaan Informasi” dan “Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Perdagangan Orang Dalam”. Oleh karena itu, sembilan pegawai PGAS didakwa atas pelanggaran terhadap pasal 95 yang berbunyi:
“Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek:
- Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau
- perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.”
Pada akhirnya, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) mengenakan sanksi administratif kepada kesembilan oknum orang dalam PGAS, yang berkisar antara Rp9 juta-2,33 miliar sesuai dengan besaran pelanggaran yang diperbuat.
Kasus Kejahatan Pasar Modal di Luar Negeri
Ketika membahas kecurangan pasar modal luar negeri, pasar modal Amerika Serikat pernah mengalami sebuah kasus fraud oleh sebuah korporasi dengan kapitalisasi pasar sebesar 60 juta dolar AS. Kasus fraud ini terjadi pada emiten bernama Enron, sebuah emiten yang didirikan di tahun 1985 dan bergerak di industri energi. Enron dibentuk dari merger dua perusahaan gas alam, Houston Natural Gas Corporation dan InterNorth Inc, pada tahun 1985 diprakarsai oleh CEO Houston Natural Gas Co. saat itu, Kenneth Lay. Perusahaan hasil merger ini kemudian diberi nama HNG InterNorth, sebelum diubah kembali menjadi Enron pada tahun 1986.
Kejayaan Enron dimulai ketika Kenneth Lay menunjuk Jeffrey Skilling menjadi CEO di tahun 1990. Berada di tangan Skilling, Enron mengalami peningkatan performa keuangan secara signifikan. Salah satu langkah Skilling dalam meningkatkan produktivitas SDM adalah dengan menerapkan sistem rating yang diberi nama “rank and yank“. Setiap tahunnya, karyawan akan dievaluasi dan dikelompokkan menjadi lima kelompok berdasarkan performa. Sebanyak 15% karyawan yang masuk ke dalam kategori “need improvement” di Enron berpotensi untuk mengalami pemecatan dalam enam bulan ke depan. Strategi “rank and yank” ini mendorong karyawan Enron bekerja sangat keras hingga 18 jam sehari untuk memenuhi standar yang diberikan.
Di balik kejayaannya, petinggi Enron mulai merencanakan kecurangan finansial dengan mengajukan sebuah metode pencatatan akuntansi yang disebut mark-to-market accounting, sebuah metode untuk mencatat aset dengan harga pasar (fair value). Metode ini menjadi kunci penting bagi Enron dalam melakukan kecurangannya. Enron yang merupakan perusahaan energi (energy-trading) dapat memanipulasi laporan keuangan dengan mencatat proyeksi laba (estimated profit) menjadi laba (actual profit). Contohnya, apabila hari ini Enron menekan kontrak perdagangan senilai 50 juta dolar AS untuk 10 tahun ke depan, Enron akan langsung mencatat 50 juta dolar AS sebagai pendapatan hari ini. Disebabkan memiliki model bisnis sebagai perusahaan trading, nilai dari kontrak Enron pun sangat subjektif sehingga Enron dapat dengan leluasa menetapkan”fair value” dari kontrak tersebut pencatatan ini membuat Enron tampak profitable dan terlihat memiliki pendapatan fantastis di atas kertas.
Dalam menutupi jejak minimnya arus kas akibat manipulasi keuangan, CFO Enron, Andrew Fastow mengambil langkah dengan mendirikan banyak Special Purpose Vehicles (SPVs). SPV merupakan sebutan untuk perusahaan-perusahaan kecil yang didirikan oleh korporasi besar dengan tujuan untuk menyelesaikan proyek tertentu. Melalui SPV, Enron mengalihkan aset-aset bermasalah untuk menghapus jejak manipulasi keuangan. Sebagai akibat dari SPV yang dibangun oleh Enron dicatat sebagai perusahaan privat, tidak ada ekspos mengenai keadaan internal perusahaan-perusahaan kecil tersebut kepada para analis dan publik. Padahal, mayoritas SPV yang dimiliki Enron hanyalah perusahaan “di atas kertas” atau perusahaan fiktif.
Ambisi Enron terus berlanjut dengan melakukan akuisisi terhadap perusahaan listrik swasta California, Pacific Gas and Electric Company (PG&E). Di bawah kendali Enron, pemadaman listrik bergilir makin sering terjadi di California yang membuat banyak warga protes. Namun, tampak tidak banyak langkah yang dilakukan pemerintah saat itu. Dilansir dari The New York Times, George W. Bush, presiden AS yang saat itu menjabat, menolak untuk melakukan intervensi terhadap cara Enron menjalankan bisnis listriknya dengan alasan tidak ingin pemerintah campur tangan berlebihan di pasar bebas.
Kejatuhan Enron dimulai ketika Jeffrey Skilling mengundurkan diri dari posisi CEO pada tanggal 14 Agustus 2001. Mundurnya Skilling dari bangku CEO menjadi tanda tanya besar bagi publik karena Skilling dinilai sebagai alasan Enron dapat berada di posisi kejayaannya saat itu. Tepat sehari setelah mundurnya Skilling, Sherron Watkins yang saat itu menjabat sebagai Vice President Enron mengirim surat secara anonim kepada Kenneth Lay yang menjadi CEO berisi laporan tentang malpraktik di dalam Enron. Surat tersebut memperingatkan akan terjadi “ledakan” di masa yang akan datang. Seiring waktu berjalan, publik semakin bertanya-tanya mengenai keadaan Enron sebenarnya sehingga mendorong Lay tampil di depan publik untuk menenangkan keadaan. Berbagai kejanggalan ini membuat para analis mulai menurunkan rating saham Enron yang membuat harga saham Enron jatuh menuju 52-week low. Pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron merilis laporan kuartalan rugi pertama sejak didirikan. Laporan tersebut juga menyebutkan ditutupnya salah satu SPV bernama Raptor 1 yang menarik perhatian U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Kejanggalan kembali terjadi dengan diubahnya aturan dalam akun pensiun yang membatasi karyawan untuk menjual saham. Tidak lama berselang, SEC mengumumkan bahwa mereka sedang melakukan investigasi terhadap Enron dan berbagai SPV yang didirikan oleh Andrew Fastow.
Hasil investigasi Departemen Kehakiman AS menyebutkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2002, Pimpinan Arthur Andersen LLP yang menjadi kantor akuntan Enron, David Duncan, memerintahkan karyawannya untuk menghancurkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan Enron untuk menghapus barang bukti praktik fraud. Setelah berbagai investigasi dilaksanakan, terbongkar malpraktik yang dilakukan oleh Enron dengan terungkapnya kerugian sebesar 591 juta dolar AS dan utang sebesar 690 juta dolar AS pada tahun 2000. Tidak lama berselang setelah terungkapnya malpraktik di dalam Enron, pada 2 Desember 2001, Enron menyatakan bangkrut yang menimbulkan kerugian sebesar 74 miliar dolar AS kepada para pemegang saham. Kasus ini ditutup dengan dipenjarakannya mantan CEO Enron, Jeffrey Skilling, Chairman sekaligus CEO, Kenneth Lay, dan CFO Enron, Andrew Fastow.
Dunia Belajar dari Enron
Skandal Enron yang menimbulkan shock di pasar keuangan AS menjadi sebab munculnya Sarbanes-Oxley (SOX) Act of 2002, sebuah kompilasi hukum yang disusun untuk melindungi investor dari kecurangan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh sebuah korporasi. Dalam SOX, setiap korporasi dituntut untuk memiliki auditor independen yang bertindak mengevaluasi struktur internal dan pelaporan keuangan perusahaan. SOX juga berisi perlindungan terhadap whistleblower, larangan diberikannya pinjaman kepada eksekutif perusahaan, hingga diikatnya eksekutif terhadap laporan keuangan dengan diwajibkan membubuhkan tanda tangan pertanggungjawaban pada laporan yang dirilis perusahaan.
Sarbanes-Oxley (SOX) Act of 2002 pada awalnya dinilai sebagai sentimen negatif karena dianggap memberatkan korporasi. Namun seiring waktu berjalan, SOX mulai diterima publik dan dinilai mampu melindungi investor dari oknum eksekutif korporasi yang tidak bertanggungjawab.
Penutup
Risiko kerugian merupakan faktor yang tidak bisa lepas dari sebuah investasi. Tidak dapat dimungkiri, berbagai risiko yang dihadapi tidak semuanya dapat berada di bawah kendali kita, sebab terdapat pula risiko-risiko yang berada di luar kendali. Sebagai investor, kita perlu fokus untuk memperhatikan apa saja risiko yang dapat kita kendalikan, salah satunya literasi. Kecakapan dalam literasi keuangan akan menghindarkan kita dari kasus kejahatan pasar modal lain di masa depan. Adapun, untuk faktor risiko yang berada di luar kendali kita, seperti kejahatan pasar modal yang terjadi di PGAS dan Enron, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk untuk memitigasi hal seperti ini terulang kembali. Oknum-oknum tidak bertanggungjawab selalu memiliki cara baru dalam melakukan kejahatannya dan OJK berperan besar untuk melindungi investor di masa yang akan datang.
Referensi
Ambarwati, M. D. (2022). Crimination of fraud crimes in capital market transactions. Yuris Journal of Court and Justice, 1–13.
Anisa, P. (2022, March 2). Mengenal Insider Trading dan Kasusnya di Indonesia – Ajaib. PT Takjub Teknologi Indonesia. https://ajaib.co.id/mengenal-insider-trading-dan-kasusnya-di-indonesia/#1_PT_Perusahaan_Gas_Negara_Tbk_PGAS
Bareksa Portal Investasi. (n.d.). Insider Trading – Pengertian, Arti, dan Definisi. Bareksa.Com. Retrieved August 24, 2022, from https://www.bareksa.com/kamus/i/insider-trading
dob. (2021, October 11). Ada 5.000 Kasus Perbulan, Indonesia emergency Kejahatan Siber. cnbcindonesia.com. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211011205453-37-283113/ada-5000-kasus-perbulan-indonesia-emergency-kejahatan-siber
Ganti, A. (2022, June 20). What is insider trading? Investopedia. https://www.investopedia.com/terms/i/insidertrading.asp
Sambuaga, D. (2016). KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DI BIDANG PASAR MODAL DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1995. LEX PRIVATUM, 4(5). https://doi.org/12653
The Investopedia Team. (2022, July 8). Poop and scoop definition. Investopedia. https://www.investopedia.com/terms/p/poopandscoop.asp
Prastiwi, I. A. (2020). Perdagangan orang dalam (insider trading) Dalam Transaksi Saham di PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. Widya Yuridika, 3(1), 53. https://doi.org/10.31328/wy.v3i1.1210
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, 95 (1995). https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal.aspx
US Securities and Exchange Commision. (n.d.). Pump and dump schemes. In Investor.gov. Retrieved August 24, 2022, from https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/glossary/pump-and-dump-schemes
Bondarenko, P. (2022, August 13). Enron scandal. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/event/Enron-scandal
Committee on Energy and Commerce House of Representatives. (2002, January). – Destruction of Enron-related documents by Andersen personnel. GovInfo. https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-107hhrg77569/html/CHRG-107hhrg77569.html
LCG Consulting. (2001, August). A shocker: Enron’s Jeff Skilling resigns. LCG Consulting :: EnergyOnline. http://www.energyonline.com/Industry/News.aspx?NewsID=5042&A_Shocker%3A_Enron%27s_Jeff_Skilling_Resigns
Miles, J. (2021, December 3). “Justice was served”: Enron whistleblower reflects on 20th anniversary of company’s collapse. KHOU. https://www.khou.com/article/money/business/enron-whistleblower-20th-anniversary/285-f0c3ad1a-3c31-4511-bfc6-5372b1196f24
Ross, B. (2002, January). Enron destroyed documents by the truckload. ABC News. https://abcnews.go.com/WNT/story?id=130518&page=1
Segal, T. (2022, July 13). Enron scandal: The fall of a wall street darling. Investopedia. https://www.investopedia.com/updates/enron-scandal-summary/
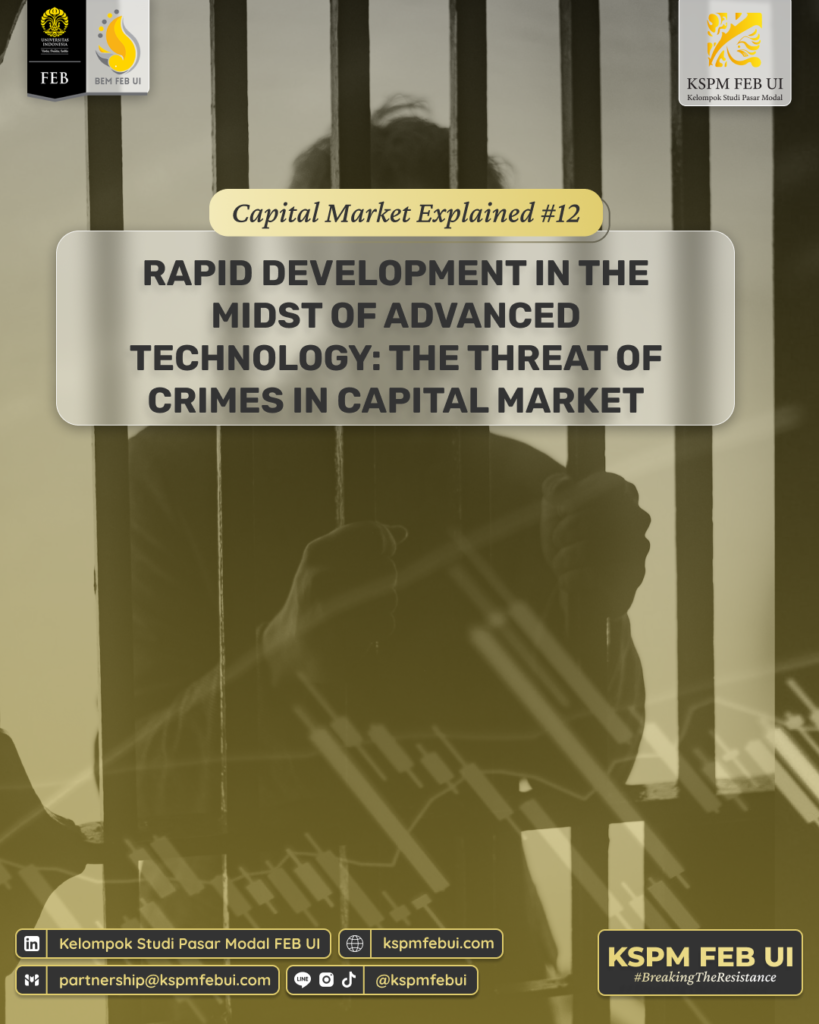
Written by:
Research and Development Division
Grace Eva Rosana
Habel Abraham B.S.
Gayska Vetotama
Published by:
Operation and Infrastructure Division
Nadhifa Raihani
nadhifa.raihani@ui.ac.id